Anak muda jalanan Solo: Kalau kau melihatnya dari atas ketinggian sekitar 200 meter, dalam arus spotlight video, dengan garis-garis pijar cahaya yang bergerak terus dalam 24 jam, blur cahaya yang memanjang membentuk pelangi malam, kami hanya titik-titik yang singgah di malam hari di pinggir jalan pusat kota. Hanya di malam hari dan memang kebanyakan hanya di malam hari tapi bukan yang mendominasi jalan. Kami merasa ada. Di jalan raya. Di pinggir jalan raya ini kami bisa bersama teman, sahabat, juga kekasih, tapi kebanyakan bukan keluarga. Sesekali ditemani obrolan, bukan diskusi, kuliah, ,orasi, apalagi ceramah. Cukup obrolan, yang biasa saja, dan sesekali kami membuat potret diri kami yang berada di pinggir jalan raya ini. Dan tentu saja kita tersenyum di jalan raya ini.
Lampu-lampu kota memang lebih menghias dan menyentuh di malam hari. Manusia lebih suka yang temaram daripada sinar matahari yang bisa membuat jengah dan jengkel. Lebih suka menakjubi ciptaan manusia daripada ciptaan Tuhan. Dan pusat kota Solo menyediakan semua itu. Meski kami di pinggir jalan, seperti yang kami alami tiap kali kami berada di pinggir jalan Kota Solo ini. Tapi itu sudah cukup. Manusia memang sering hanya berada di pinggir jalan, di dunia ini. Bahkan terkadang memang tidak begitu jelas apakah manusia benar berada di jalan atau hanya di pinggir jalan.
Di jalan ini, antara jalan Slamet Riyadi dan jalan Jenderal Sudirman, di depan bangunan Bank Indonesia baru yang sedikit bertaman dan berlampu, di depan Kantor Pos Indonesia, Gereja Penabur Solo, Bank Bukopin, juga benteng Vastenberg sisa kekuasaan kolonialisme Belanda yang sudah tertutup malam, kami ada dan berkumpul. Hampir tiap malam. Tanpa intervensi bangunan-bangunan itu malam ini dalam memori sejarah malam kami. Kehadiran jalan ini lebih berarti bagi kami, daripada bangunan-bangunan penuh kekuasaan itu. Kehadiran bok jalan, atau sebanarnya adalah bata pemagar taman kota, sudah cukup untuk kami malam ini. Hidup harus cukup dengan yang ada, dan kota sudah terlalu cukup untuk kami, malam ini.
Kami tidak ingin melihat, mengenang, atau mengingat, apalagi yang sudah silam, masa lalu, dan sudah berlalu. Apalagi mengingat tentang sejarah bangunan kota, juga sejarah jalan yang ada dan kami singgahi ini. Kami ingin diingat, dilihat, juga mungkin dikenang. Tapi bukan sebagai anak jalanan ala Ali Topan. Tidak, sebenarnya kami hanya ingin menikmati, merasakan yang terkini, dan di sini ini. Singgah. Hidup ini, yang sebentar lagi beranjak. Mungkin kami hanya ingin menghidupi malam seperti yang dikatakan filosof eksistensialisme Jean Paul Sartre, “We have only this life to live.” Ya tiap manusia hanya hidup sekali dan hanya itulah hidupnya. Ah, sepertinya tidak, bukan kehidupan. Kehidupan itu terlalu besar dan tampak berharga sekali. Yang kita punya hanya momen-momen yang ingin kita habiskan bersama, di sini, di tempat ini, mala mini, di pinggir jalan Jenderal Sudirman ini.
Dan jika saya menggunakan pronominal kami, atau anak muda lainnya, bukan berarti hendak menggeneralisir. Bukan kami sebagai semua yang hadir dan ada di jalan raya ini, tapi hanya ‘kami’ yang kami kenal: teman-teman kami saja. Kami yang ada di sini ini tak saling kenal dan tak ingin saling kenal lebih jauh. Hanya sebentuk kebetulan dan kesempatan yang membuat kita menaiki motor, sepeda, atau mobil kami sehingga kami bisa bersama. Hanya bersama, sekilar bertatap muka, bukan pertemuan yang intens. Jalan dan ruang ini mempertemukan tubuh kami. Hanya tubuh yang dipertemukan jalan. Bukan sebuah gagasan, ide, atau ideologi. Hanya ruang. Tapi, siapa yang bisa mengelak ruang dalam hidup ini? Ruang ini hadir, mengada, untuk kami singgahi. Ini adalah ruang jeda. Hidup memang terus berjalan tanpa bisa kita semua hentikan, dan kami membutuhkan ruang dan waktu jeda. Malam ini, di jalan raya ini.
Di setiap jalan, manusia hanya lewat, siapa pun dia. Tak lebih, tak kurang. Ya, mungkin kau teringat tentang arsitek yang merancang jalan dan kota, mahasiswa yang memikirkan tentang struktur jalan raya, para pekerja di Departemen Pekerjaan Umum yang berkeringat, atau kontraktor yang mengerjakan jalan ini, semuanya pada akhirnya hanya melewati jalan ini. Semua manusia hanya melewati jalan. Dan bisakah manusia lebih daripada melewati jalan? Mungkin, seperti membuat jalan atau membersihkan jalan, atau memberi jalan pada yang lewat. Tapi, yang kami lakukan malam ini adalah di antara melewati dan berhenti untuk menikmati jalan. Namun, lebih tepat jika kami mengatakan hanya sebagai menumpang jalan ini. Kita mengada di pinggir jalan, tak hendak melewati begitu saja.
Itulah kenapa, di jalan ini kami hanya ingin semacam memarkir sepeda motor kami, berjejer, bukan mengendarainya. Apalagi mengendarainya dengan suara mesin dan knalpot yang berteriak. Orang-orang, yang kami tidak kenal, melewati jalan ini di atas kendaraan mereka. Mereka kemungkinan besar tidak menyadari kehadiran jalan, mereka tak menikmati dan tak mensinggahi jalan. Yang barangkali menyadari adalah mereka—juga seperti kami—yang mengayuh sepeda onthel yang harus merasakan kayuhan. Mereka menikmati jalan, mengayuh pelan-pelan, sambil tersenyum dan ngobrol dengan sesama pengendara onthel. Ini adalah semacam menikmati jalan raya, bukan menggunakannya.
Jalan raya yang kita berada di pinggirnya ini akan menjadi semacam memori kolektif kebersamaan anak muda (juga beberapa manusia dewasa yang sudah punya anak-istri-suami). Tapi, bukan untuk kita kenang dengan heroik seperti yang dilakukan para demonstran yang menikmati jalan di Gladak ini dengan megafon yang berteriak, poster yang merajuk atau mengecam, atau iringan barisan manusia yang tegang dalam seremoni kultural. Di jalan ini kami hanya ingin menikmati, bukan memprotes. Yang kami lakukan bukan protes, bukan menuntut, juga bukan merajuk. Barangkali kami hanya ingin yang sederhana: menikmati lampu kota, bukan langit dengan bintang-bintang atau bulan saat malam terang.
Ini bukan politik okupasi jalan raya pusat kota atau pertarungan strategi geografis seperti memperebutkan bangunan strategis di pusat kota untuk bisnis. Barangkali, ini hanya sekadar politik representasi simbolis anak muda Solo. Demi malam, demi lampu kota, atau demi penjual bakso bakar yang sesekali diusir petugas. Dan tentu saja demi menikmati jalan raya kota. Anda juga boleh menikmati jalan raya pusat kota kita ini.




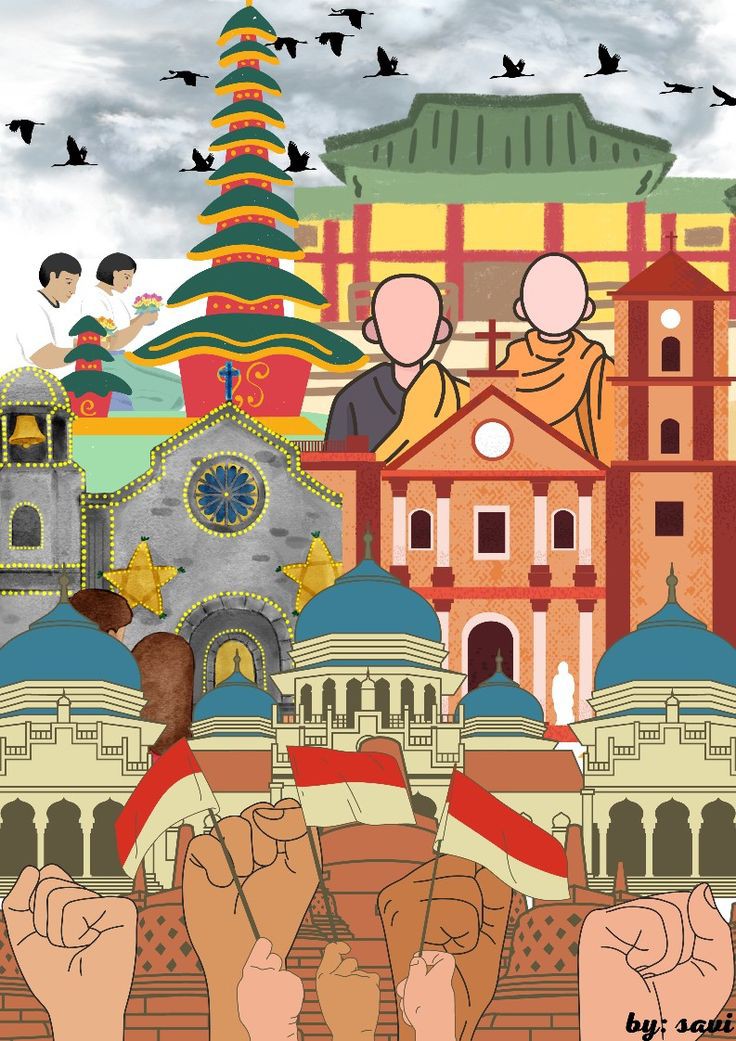



Add comment