Sepucuk Nasihat Untuk Wayangnya
Rahman dengan berjinjit pelan membawa dua butir telur ayam kampung solo di genggaman tangan kanannya. Tangan kirinya meraba-raba selusur papan kandang. Celana bersulam mobil-mobilnya terkena bercak lumpur di mana-mana. Sementara, pipi montok menggemaskan itu sekarang seperti muka prajurit Indian, tercoreng dua saput kotoran. Entah oleh apa, bisa jadi oleh tahi ayam. Tampang serius sekali membawa telur-telur itu. Ibunya berdiri mengamati, tersenyum sambil memungut telur di rak yang lebih tinggi.
Sayang sekali sebelum ia tiba di ember besar yang di letakkan di sebelah kaki Ibunya, seekor ayam jantan soloensis entah dari mana asalnya, terbang masuk kandang ensis. Berkotek menyergap tubuh Rahman yang menginjak umur 16 tahun. Pria itu Berseru kaget. Telur-telur di genggaman tangannya terlepas, terlontar entah ke mana. Rahman untuk sepersekian detik bisa mendengar telur itu satu per satu jatuh menghantam lantai semen. Seperti bisa melihat tetesan air jatuh dari lagnit secara patah-patah. Dan telur-telur ringkih itu pecah tak keruan. Sambil menahan sakit di lututnya pria meninggalkan masa kecil itu mencoba berdiri. Matanya berkaca-kaca. Ia meraba-raba, tertatih melangkah, mendekati kaki Ibunya takut-takut. Sebentar lagi pria itu pasti merengek.
Tetapi Ibunya tidak marah. Justru duduk jongkok menyambut anaknya itu. tersenyum, mengahapus buliran air mata di pipi Rahman. Menatapnya amat bijak, kemudian memegang bahunya dengan lembut.
“Jangan dipikirkan. Hanya telur, Anakku Sayang!” Tetapi Rahman tetap terisak. Ibunya sambil menghela napas dalam-dalam, perlahan duduk selonjor di lantai lorong kandang ayam. Ia menepuk-nepuk bulu ayam di pakaian bidadara kecillnya. Lantas mendudukkan Rahman di pangkuannya. Topi jerami itu ia sangkutkan di sembarang tempat.
Di rumah ini, Rahman hanya tinggal dengan Ibunya seorang. Tidak ada siapa-siapa lagi. Dulu Ayah masih ada rumah ini ramai sekali. Tetapi Ayah di panggil sang Kholik. Ayah meninggalkan dengan kenangan getir dan apabila diingat lagi, hati ini terasa miris dan sedih. Apalagi Rahman yang sedang tumbuh dengan segala kepolosan hidup. Ia punya Ibu yang siap mengganti peran Ayahnya di jagat raya ini.
“Tahukah, Sayang. Jika kau melemparkan sebutir telur dari atas awan, saat jatuh menimpa tanah, sedikit pun telur itu takkan retak sepanjang kau punya sesuatu!” Ibunya berbisik di telinga Rahman. Beginilah yang Ia selalu membisikkan kisah-kisah indah karena suatu saat ia yakin Rahman berhak atas manisnya kehidupan ini. Dan Pria mungil itu seperti biasa, mendongakkan kepalanya penuh rasa ingin tahu, mengerjap-ngerjapkan mata bulatnya, lantas menggeleng. Saat-saat seperti ini selalu menyenangkan baginya.
“Dan tahukah kau apakah sesuatu itu?”
Rahman menggeleng yang kedua kalinya.
“Sesuatu itu adalah cinta!”
Ibu menyebut perlahan dan penuh perasaan kata itu. seperti mengantungnya menjadi bintang di langit-langit kandang. Rahman justru berpikir tentang hal lain.
“Kalalu begitu cinta itu seperti kasur, ya, Bu? Yang saat Rahman loncat-loncat di atasnya tidak terasa sakit?”
“Bukan. Cinta itu tidak seperti kasur, Sayang”
“Jadi bagaimana ia membuat telur itu tidak pecah?”
“Karena cinta itu akan memberikan sepayang sayap yang indah kepada telur itu, Sayang.” Ibunya tersenyum sambil menciumi ubun-ubun pria itu.
“Jadi cinta itu seperti burung!”
“Ya. Seperti burung. Ia akan membawamu terbang ke mana saja. Membuatmu bisa memandang seluruh isi dunia dengan suka cita; Bahkan, terkadang kau merasa seluruh dunia ini hanya milikmu semata.”
Pria itu ikut-ikutan mendongakkan kepala menatap kosong langit-langit kandang. Membayangkan mendengar kepak-kepak sayap burung yang sama sekali belum pernah dilihatnya. Sepertinya itu amat menyenangkan.
“Ibu, Rahman ingin cinta!”
Kemudian, hari-hari berikutnya Rahman jadi sering sekali bertanya tentang cinta. Suatu pagi, saat ia berlatih bernyanyi do-re-mi sambil belajar berdansa, patah-patah memegang tangan renta Ibunya, Rahman menyela, “Ibu, apakah cinta itu menyenangkan seperti musik?”
“Ya. Ia seperti musik, tetapi cinta sejati akan membuatmu selalu tetap menari meskipun musiknya telah berhenti.”
“Kalau begitu, Rahman ingin cinta!”
Ibunya tersenyum meringis sambil memijat-mijat pinggangnya. Pria mungilnya tidak tahu, berputar-putar menari seperti ini membuat encoknya kumat lagi.
Suatu ketika, Rahman duduk menggigil malam-malam katakutan, badai mengamuk di luar sana. Angin menderak-derakkan jendela. Kilat dan guntur susul-menyusul memekakkan. Rahman yang baru terbagun dari mimpi buruk hantu-hantu, mendongak ke arah Ibu yang sedang memeluknya. “Buk, apakah cinta itu mankutkan seperti hantu?”
“Ya, cinta seperti hantu. Semua orang membicarakannya, tetapi sedikit sekali yang benar-benar pernah melihatnya.”
Rahman mengeryitkan dahinya. Mengkerut takut dalam pelukan Ibunya. “Kalau begitu, Rahman tidak ingin cinta lagi!”
Ibunya tersenyum merasa bersalah. Malam ini ia terlalu lelah. Dari tadi ingin rasanya segera tidur. Tetapi putra sematang wayang yang sedang ketakukan sepertinya tak akan beranjak menutup matanya. Mungkin dengan begini putranya bisa segera terlelap.
Ketika paginya mereka berdua berendam dalam sejuknya air sungai di belakang peternakan. Rahman yang senang sekali memukul-mukul air ke arah ibunya. Di antara percikan air yang bening, tiba-tiba menyela, “Ibu apakah cinta sesejuk air sungai ini?”
“Ya. Cinta sejati memang seperti air sungai, sejuk menyenangkan, dan terus mengalir. Mengalir terus ke hilir tidak pernah berhenti. Semakin lama semakin besar karna semakin lama semakin banyak anak sungai yang bertemu. Begitu juga cinta, semakin lama mengalir semakin besar bantang perasaannya.”
“Kalau begitu ujung sungai ini pasti ujung cinta itu?”
“Cinta sejati adalah perjalan, sayang. Cinta sejati tak pernah memiliki tujuan”
“Ibu, apakah cinta itu memberi, seperti yang selalu Ibu lakukan saat memberi makan ayam-ayam?”
“Tidak. Karena kau selalu bisa memberi tanpa sedikit pun memiliki perasaan cinta, tetapi kau takkan pernah bisa mencintai tanpa selalu memberi.”
“Ibu, dari kota makanah cinta datang?”
“Tidak ada yang athi, Sayang. Cinta sejati datang begitu saja, tanpa satu alasan pun yang jelas!”
“Kalau begitu bagaimana Rahman tahu cinta?”
“Kau akan tahu ketika ia datang. Tahu begitu saja. Dulu orang-orang menyebutnya cinta pandangan pertama. Cinta sejati selalu datang pada pandangan pertama. Cinta sejati selalu datang pada saat yang tepat, waktu yang tepat, dan tempat yang tepat. Ia tidak pernah tersesat. Cinta sejati selalu datang pada orang-orang yang berharap berjumpa padanya dan tak pernah berputus asa.
“Kelak saat kau dewasa, kau akan melihat banyak sekali orang-orang yang begitu saja jatuh cinta. Bagi mereka, cinta seperti memnubgut bebatuan di pinggir sungai. Banyak bertebaran. Bosan bisa dilemparkan jauh-jauh. Kurang, tinggal memasukkan batu yang lain kedalam kantong lainnya. Apakah perangai seperti itu disebut cinta? Tentu saja bagi mereka juga cinta. Tetapi ingatlah selal Rahman-ku, cinta sejati tak sederhana bebatuan.”
“Suatu saat jika kau beruntung menemukan cinta sejatimu. Ketika kalian saling bertatap untuk pertama kalinya, waktu akan berhenti. Seluruh semesta alam takzim menyampaikan salam. Ada cahaya keindahan yang menyemburat, menggetarkan jantung. Hanya orang-orang beruntung yang bisa melihat cahaya itu, apalagi berkesempatan bisa merasakannya.”
“Apakah Ibu pernah bertemu dengan cinta?” Ibunya tertawa pelan sambil mengelus rambut lurus lelaki sematang wayang dalam hidupnya sekarang. Rahman tersenyum, ia sudah terbiasa dengan jawaban tawa pelan seperti itu.
“Apakah cinta memerlukan mata untuk memandang?”
“tentu tidak, Sayang!”
Ibu mencium khidmat ujung-ujung jari mungil Rahman. Rahman tersenyum, ia juga sudah terbiasa dengan jawaban cium ujung-ujung jari seperti itu.

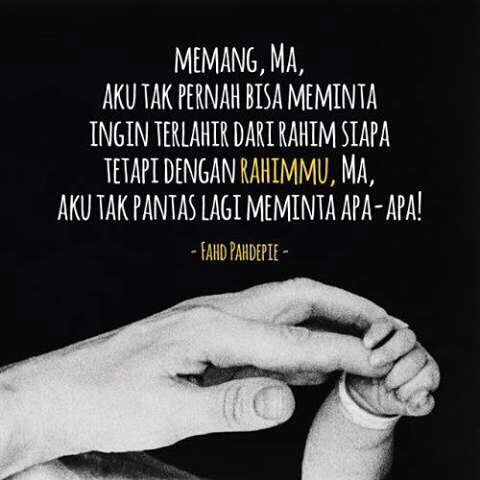




Add comment