Seorang teman istri saya pernah bertanya perihal alasan memilih sekolah inklusi untuk anak pertama kami. Begini pertanyaannya. “Hlo, anakmu kan normal, kok bisa memilih sekolah yang bareng anak-anak (maaf) cacat (anak berkebutuhan khusus)?” Apa justru tidak mengganggu proses belajar mengajar?” Dua pertanyaan itu diakhiri dengan satu pernyataan tegas darinya. “Kalau saya akan berpikir dua kali untuk menyekolahkan anak saya di sekolah semacam itu.”
Istri saya hanya tersenyum. Bingung juga dia mau menjelaskan dari mana karena dari sudut pandang saja sudah jelas berbeda antara dia dan temannya mengenai sekolah inklusi dan anak berkebutuhan khusus (ABK).
Pertanyaan atau lontaran itu tidak sekali dua kami temui saat berbincang dengan orang tua lainnya. Ada diskusi di situ, ada perbedaan pandangan yang didasarkan pemahaman, referensi, dan nilai-nilai yang diyakini. Wajar saja. Toh kita memang hidup bukan untuk mencari keseragaman dalam hal apa pun. Saya juga menghargai setiap orang tua yang pasti memilihkan sekolah yang terbaik untuk putra putrinya.
Di sini saya sekadar ingin berbagi mengenai alasan mengapa memilihkan sekolah inklusi untuk anak. Seperti di tulisan saya sebelumnya di Soloensis (Sekolah itu Menyenangkan), saya menginginkan anak saya memahami keberagaman dan perbedaan dari awal. Salah satunya dengan memasukkannya di sekolah inklusi di SD Tumbuh 2 Jogja. Di sekolah ini, setiap kelas terdapat 1-2 siswa anak berkebutuhan khusus. Mereka dibaurkan dengan siswa-siswa lainnya, meski tentu saja materi pelajaran dan soal yang diberikan berbeda. Dalam satu kelas yang terdiri maksimal 22 siswa itu, ada tiga guru yang mengampu. Perinciannya, dua guru mengampu anak-anak yang normal, satu guru mendampingi ABK.
Pendidikan bukan sekadar mengajarkan mata pelajaran agar anak-anak menjadi paham. Pendidikan dalam kacamata saya adalah bagaimana anak-anak mendapat internalisasi nilai-nilai dalam hidup sejak dini, termasuk menghargai perbedaan. Dengan adanya pembauran siswa di kelas, anak-anak yang tidak berkebutuhan khusus dididik untuk bisa menerima kawannya yang ABK dan saling tolong-menolong. Mereka juga bermain bersama-sama. Tidak ada tatapan aneh dari anak-anak jika melihat teman mereka berbeda. Pemahaman akan perbedaan ini perlu ditanamkan sejak dini agar benar-benar mendarah daging dalam diri mereka, sebab di luar sana hidup memang banyak perbedaan dan tidak bisa selalu seragam.
Contohnya, suatu ketika saya duduk-duduk di kantin sekolah, menunggui anak saya yang sedang mengikuti klub (ekstrakurikuler) aikido. Dua gadis dengan wajah riang berbincang dengan bahasa isyarat. Keduanya tunarungu. Seru sekali menyaksikan mereka ngobrol dengan asik. Tak lama, datanglah kawan-kawan mereka yang pria. Si gadis ini mencandai kawannya yang baru datang sambil tertawa-tawa. Si teman pria ini pun nimbrung dan ikut bercanda dengan mereka. Pemandangan yang indah, batin saya. Banyak contoh lain yang bisa ditemukan dalam keseharian mereka, soal menghargai perbedaan ini, termasuk saling tolong di antara ABK dan siswa lainnya.
Sekolah inklusi memang bukan sekadar label tanpa makna. Sekolah yang berani memproklamasikan diri sebagai sekolah inklusi punya tanggung jawab besar untuk benar-benar mengejawantahkannya dalam program pendidikan mereka sehari-hari. Mulai dari tenaga pendidik—yang wajib tahu cara menangani kelas inklusi–, sarana dan prasarana yang mendukung, hingga orang tua siswa yang juga perlu pemahaman komprehensif mengenai sekolah inklusi.
Seorang teman saya—yang anaknya berkebutuhan khusus (hiperaktif dengan energi berlebih), pernah bercerita. Dia dulu menyekolahkan anaknya di sebuah sekolah, sebelum di sekolah yang sekarang. Di kelas, sang guru mengaku kewalahan dalam mendidik sang anak, yang kadang tiba-tiba keluar sendiri dari kelas, duduk di luar kelas, dan sebagainya. Intinya, teman saya dipersilakan mencari sekolah lain karena gurunya tidak sanggup mendidik ABK.
Sekarang, anak ini sudah duduk di kelas III. Dia mengatakan ada perkembangan positif dalam diri anaknya. Energi berlebihnya sudah bisa disalurkan lewat hobi, di sekolah juga tidak lagi suka keluar kelas sendiri, atau mogok belajar, atau bikin gaduh. Teman-temannya juga diajari bagaimana cara bergaul dengannya. “Saya bersyukur ada perubahan positif pada anak saya,” begitu kata teman saya.
So, kesimpulannya, menanamkan nilai-nilai untuk menghargai adanya perbedaan semestinya dilakukan sejak dini, dan sekolah inklusi adalah salah satu wahana yang tepat untuk melatih anak-anak akan hal tersebut. Tentu saja kita sebagai orang tua juga harus lebih dulu memahami dan mengerti akan perbedaan karena terkadang, justru orang tua yang lebih susah menerima perbedaan daripada anak-anak kita.
Sekolah Inklusi Mendidik Anak Menghargai Perbedaan


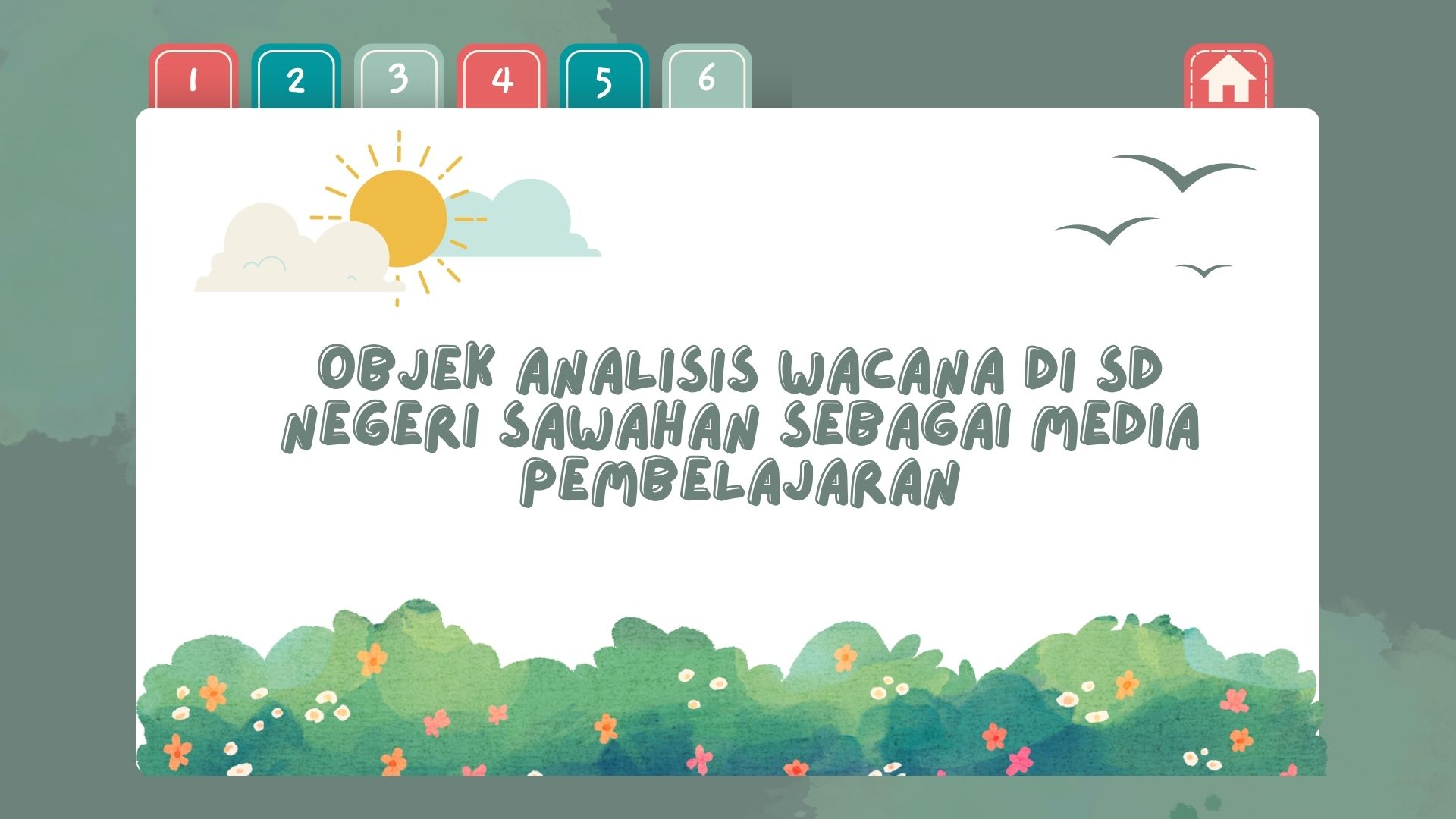





Add comment