Balada Sang Pengantin
Tubuhnya yang mengurus telah digelayuti hawa dingin. Kulit kuning langsatnya memucat, tak lagi cerah. Bola mata lebarnya yang jernih umpama sebutir kelereng tak mampu terbuka lagi. Ia telah terbujur kaku, nyawa tak lagi dikandung badannya.
Sungguh tak ada yang menyangka kapan ajal tiba. Ahad (16 September 2012) malam kemarin wajahnya masih bertabur senyuman. Ia bersemangat menjabat tangan setiap tamu yang hadir. Malam itu, ia resmi dipersunting Roni. Pemuda dari desa tetangga yang telah dikenal sebelumnya.
Kebaya putih berlengan panjang dikenakannya berpadu dengan bawahan kain batik yang lazimnya disebut jarik oleh masyarakat Jawa. Kepalanya dibalut jilbab putih dengan bando bunga melati bertempel beberapa mawar merah yang memanjang hingga pinggangnya. Wajah tirusnya diselimuti bedak yang membuatnya semakin tampak cerah. Gincu merah merona menutupi bibir tipisnya yang terus menyunggingkan senyum.
Namun betapapun sempurna riasannya malam itu tak mampu menutupi sakit fisik yang tengah ia derita. Sesekali tubuhnya yang sedikit terbungkuk gemetar dan tangannya dibanjiri keringat.
Sudah lama sebetulnya ia sakit, tapi tak tahu apa nama penyakitnya karena memang tak ditanyakan pada yang ahli. Sempat bekerja di sebuah percetakan kitab suci umat Islam, ia juga pernah bekerja sebagai buruh di pabrik rokok sebelum memilih berhenti lantaran tangannya yang selalu dibasahi keringat menyulitkannya membungkus irisan-irisan tembakau dengan kertas. Belum lagi ia sering terbatuk-batuk.
Selepas Idul Fitri lalu aku sempat bertemu dengannya. Ia memakan beberapa biskuit yang dihidangkan ibuku. Kala itu ia mampir bersama ayahnya yang merupakan adik ipar orang tuaku, suami dari adik bungsu ibu. Keduanya tak masuk, hanya duduk di depan pintu rumah orang tuaku di Kota Solo wilayah pinggiran yang tak lain merupakan masjid.
Rupanya ia mampir usai berobat di tengah persiapan pernikahannya bulan depan. Pikirku berobat di rumah sakit, ternyata ia diantar ke sebuah klinik pengobatan Cina oleh ayahnya, tentu dengan biaya tak seberapa. Selama ini permintaannya kepada orang tua untuk berobat tak mendapat sambutan.
Saat Idul Fitri jatuh pada bulan Agustus lalu, aku tak mendapati wajahnya. Sebagai anak tertua dan tak lagi memiliki orang tua, ibuku selalu mendapat kunjungan dari ketiga adiknya yang tinggal berdekatan di wilayah Boyolali pinggiran beserta pasangan dan putra-putri mereka.
Sebenarnya paman dan bibiku itu bukan orang tak berpunya. Paman bekerja sebagai buruh bangunan, sedang pasangannya bekerja sebagai buruh di sebuah perusahaan tekstil di kota yang dikenal memiliki Keraton Kasunanan. Dari pernikahan keduanya, lahir tiga orang putri. Tari yang tengah sakit adalah sulungnya.
Tari juga tak mengenyam pendidikan tinggi, ia hanya tamatan SMP, setahuku itu karena suruhan orang tuanya. Jadilah gadis kelahiran 1991 yang selalu ceria itu bekerja ketika usianya masih remaja. Ia bukanlah anak yang dimanja dengan pemberian berbagai fasilitas oleh orang tua.
Terakhir, ketika masih bekerja ia selalu hanya mengendarai kereta angin. Padahal tempatnya bekerja di percetakan Alquran ada di Solo. Ia juga jarang mengendarai Supra X keluaran 2005 berwarna hitam dengan aksen merah, kuning, dan biru milik orang tuanya.
Aku sih nggak punya motor, Budhe, yang punya orang tuaku, katanya kepada ibuku sewaktu berkunjung ke rumahnya.
Sebenarnya sudah banyak yang menasihati paman dan bibi untuk lebih serius mengobati penyakit Tari sebelum menikahkannya. Bagaimana tidak, berbulan-bulan Tari terbatuk hingga perlahan berat badannya menyusut namun tak juga ada yang tahu apa penyakitnya. Padahal ketika aku batuk sebulan pada 2008 lalu orang tuaku langsung merujuk ke rumah sakit milik Pemkot. Bronchitis, dan atas izin Yang Maha Kuasa dengan pengobatan rutin sembuh aku sembuh, walau beberapa kali kambuh.
Rabu siang (19 September 2012) sekitar pukul 14.00, ibuku mendapat tamu yang tak lain keponakan dari adik kedua ibu, remaja laki-laki. Kuketahui ia sangat akrab dengan Tari. Ke mana-mana mereka sering bersama. Ia datang bersama seorang kawannya.
“Budhe, Mbak Tari udah pergi, katanya sembari menahan air mata yang tak terbendung.
Seketika ibuku terkejut, tak menyangka, sebelum akhirnya ia bersama kakak pertamaku meluncur ke rumah Tari, aku menyusul kemudian. Tari sudah tak bernyawa. Ia dimakamkan malam hari pukul 20.00.
Status istri hanya sempat dinikmatinya tak lebih dari tiga hari. Padahal cerita bibi yang tinggal bersebelahan dengan rumahnya, saat itu mereka tengah berbincang santai, Tari masih sempat menghidangkan makan siang untuk suaminya, ia juga telah memiliki janji untuk bertemu dokter siang itu, sebelum akhirnya ia pamit sekejap untuk shalat dzuhur di kamar.
Beberapa saat menutup pintu, ia tak kunjung keluar kamar. Tak ada sahutan ketika suami dan kerabat lain memanggil namanya hingga pintupun didobrak. Tari telah terkulai tak berdaya. Ia dilarikan ke Puskesmas terdekat, sudah meninggal kata petugas medis di sana.
Memang tak ada yang mengira, malaikat maut menghampirinya di tengah kebahagiaan yang selama ini begitu dirindukan. Jatah usianya hanya 21 tahun. Selepas kepergiannya, bibiku sempat tak nafsu makan, bahkan beberapa kali kerabat menemukannya melamun sambil mengucurkan air mata. Ibuku juga harus tinggal menemaninya beberapa hari untuk merawat adik bungsunya itu.
Kini setelah hampir empat tahun kepulangan Tari, kedua adiknya lebih terurus disbanding dirinya. Namun menurut orang sekitar justru agak berlebihan, karena sedikit-sedikit pamanku minta opname ke puskesmas.
Biar nggak seperti Tari, katanya.


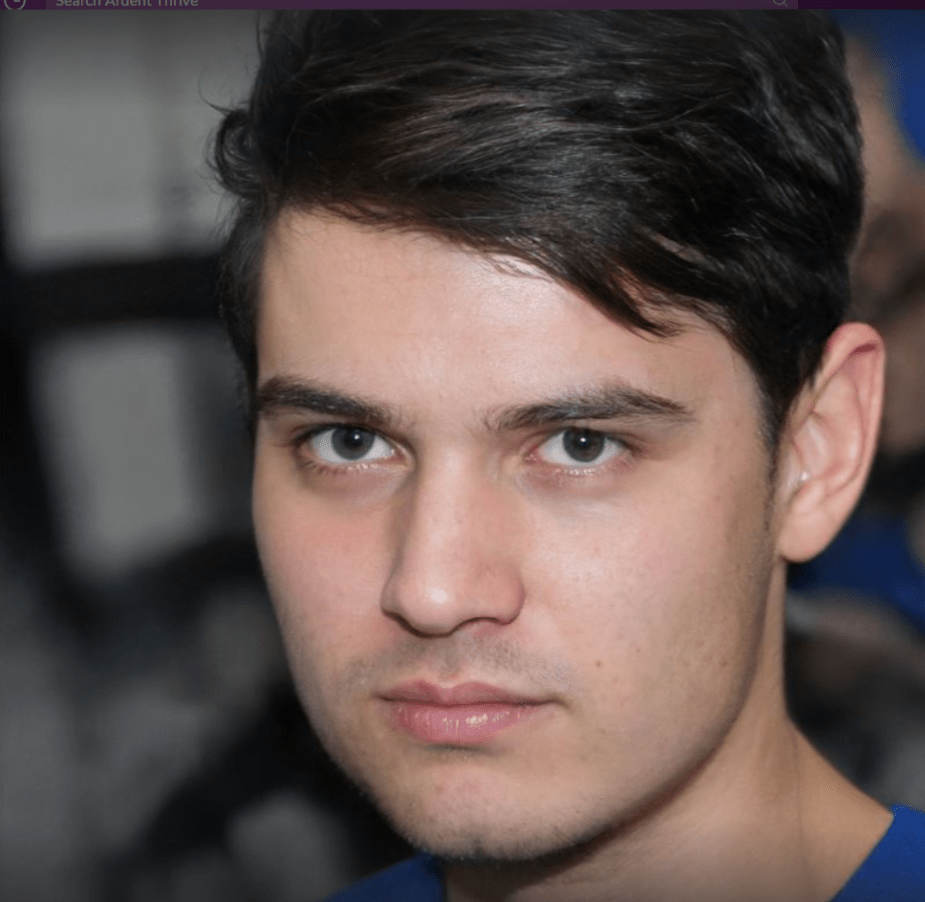
Add comment