Akademisi dari Norwegia, Johan Galtung, mengkritik media, khususnya pemberitaan media dalam situasi konflik/perang. Gavilan (2011) menulis bahwa Galtung melalui artikelnya The Structure of Foreign News pada 1965 mengemukakan media berkontribusi terhadap polarisasi konflik melalui penggunaan beberapa orientasi bahasa. Peneliti di bidang konflik dan perdamaian itu menyebut media yang memicu polarisasi masyarakat itu sebagai jurnalisme perang (war journalism). Kebalikannya adalah jurnalisme damai (peace journalism) atau jurnalisme yang berorientasi mewujudkan nilai-nilai kedamaian
Dua hal dia atas merupakan cara media membingkai yang saling berkompetisi saat meliput suasana perang maupun konflik. Jurnalisme perang berorientasi pada kekerasan, propaganda, bersifat elit dan beroreintasi pada “kemenangan”, sehingga publik sebagai dua pihak yang saling berhadapan. Jurnalisme damai adalah bingkai media yang menganalisis konflik secara lebih luas, lebih akurat, mewarnai pandangan-pandangan tentang konflik yang kemudian mentransformasikannya (Fong, 2009).
Saat ini Indonesia memang tidak dalam suasana perang. Tetapi spirit jurnalisme damai relevan untuk membingkai pemberitaan yang berorientasi pada tegaknya nilai-nilai perdamaian. Realitas sosiologis masyarakat Indonesia belakangan mengkhawatirkan. Munculnya gejala baru berupa menguatnya ikatan solidaritas kelompok (solidaritas in-group) terutama yang disatukan oleh ikatan keagamaan tertentu. Publik seolah terpolarisasi ke dalam dua kelompok yang saling berhadapan. Kelompok tertentu menjadi sangat sensitif bila kesakralan akan keyakinanya merasa diusik.
Solidaritas in-group, dalam terminologi sosiologis, akan menguat bila ada sesuatu yang dianggap “musuh” dari kelompok out-group (luar kelompok). Berbagai isu seputar Pilkada Jakarta 2017 memicu menguatnya ikatan primordialisme itu. Bila kondisi ini dibiarkan, bisa membahayakan keutuhan bangsa ini. Sosiolog Ibn Khaldun sejak abad 13 telah mengingatkan variabel ashabiyyah atau ikatan kelompok, ikatan primordialisme sebagai faktor yang dapat memengaruhi jatuh bangunnya sebuah bangsa (Alatas, 2017). Sentimen keagamaan ini kian kompleks karena banyak aktor ikut bermain dalam dramaturgi (panggungdrama) politik di Indonesia.
Saya tidak tahu apakah situasi ini akan segera berakhir, atau sebaliknya, akan terus berlangsung. Hasil Pilkada DKI Jakarta Rabu (15/2) akan sangat menentukan situasi ke depan. Apabila pemenangnya dari kelompok out-group dari kelompok mayoritas, saya memprediksi situasi ini akan berlanjut. Terlebih lagi usai Pilkada Jakarta akan segera menyusul Pilpres 2019. Meski masih dua tahun lebih, perasaan kelompok ini masih bisa digoreng seperti pada suasana saat Pilpres 2014 lalu.
Pada kondisi yang tidak menguntungkan ini, hadirnya jurnalisme damai terasa menyejukkan. Bagaimanapun media sangat berperan dalam memberi warna terhadap situasi ini—selain media sosial tentunya. Berkaca pada pemberitaan media, terutama di media online dan elektronik, belum banyak menggunakan genre jurnalisme damai dalam mengonstruksi realitas. Media sering memberitakan “perang pernyataan” meski dalam situasi kritis.
Sebagai media yang punya pengaruh besar di jagad ruang publik kita, media online dan elektronik secara etik dituntut punya tanggungjawab lebih dalam menjaga keharmonian masyarakat, bukan malah ikut arus mengikuti langgam media sosial yang nyaris tanpa aturan itu. Berdalih pada kecepatan dan keinginan mengejar tingkat “klik” dan rating, banyak media yang mengeksploitasi suasana konfliktual menjadi sekadar komoditas.
Media yang dikelola media mainstream pun, ikut mencari jalan pintas dengan menjadikan media sosial, khususnya milik para pesohor, sebagai sumber berita tanpa proses verifikasi yang cukup. Beberapa terjebak pada kabar atau akun palsu yang kemudian terpaksa meralatnya. Dalam batas tertentu, pemberitaan di media online dan elektronik mirip dengan jurnalisme “perang” ketimbang jurnalisme damai. Di artikel ini saya tidak membahas media cetak karena secara rata-rata kualitas jurnalismenya lebih bagus.
Saya sangat jarang menemukan jurnalisme yang mengonstruksi konflik dalam dimensi yang luas, kemudian mentransformasikan suasana konfliktual itu menuju titik temu. Membuat produk jurnalistik yang berkualitas membutuhkan ongkos yang tidak sedikit sehingga banyak pengelola media yang menghindari. Tidak aneh bila pengelola media online merasa puas ketika beritanya menjadi viral (menyebar luas) di internet tanpa melihat kualitas produknya. Viral seolah menjadi “agama” baru yang dapat menyokong keberlangsungan bisnis media itu. Padahal tujuan jurnalisme bukan menjadi viral, tapi lebih dari itu, punya misi yang diikat oleh bingkai kode etik yang kuat.
Mengeksploitasi kasus bernuansa SARA (suku, agama, ras) adalah haram dalam kode etik jurnalistik. Dalam ranah bisnis pun, hasrat untuk kepentingan mengejar keuntungan haruslah dalam dibingkai moral pula. Bisnis harus etis demi kepentingan bisnis itu sendiri. Semboyan ethics pay atau etika yang membawa untung layak terus kita perjuangkan (Bertens, 2013). Bukankah banyak perusahaan besar yang hancur karena skandal yang terkait etika bisnis?
Dua Pendekatan
Dalam jurnalisme, konflik memang bisa menjadi salah satu indikator nilai berita (news value). Tapi berita konflik seperti yang pas? Ini yang perlu kita renungkan.
Dalam perspektif sosilogis, kita mengenal beberapa pendekatan tentang masyarakat ideal.Di antaranya, pertama, pendekatan fungsionalisme struktural. Menurut aliran ini, masyarakat yang baik terjadi saat antarsubsistem dalam masyarakat itu bekerja secara fungsional. Aliran ini mengedepankan keharmonian dan cenderung antikonflik. Kedua, pendekatan konflik. Teori konflik—antitesis teori fungsionalisme struktural—mengatakan konflik tak selamanya buruk bagi masyarakat. Menurut Ralf Dahrendof, pentolan teori itu, konflik diperlukan guna mendorong terjadinya konsensus di masyarakat. Konflik dan konsensus jadi dua hal yang tak terpisahkan (Ritzer, 2012).
Dua pendekatan ini bisa digunakan alat analisis bagi jurnalis saat mengonstruksi realitas. Pada situasi apa jurnalis menggunakan fungsionalisme struktural dan pada situasi apa jurnalis memakai pendekatan konflik. Pada kasus yang berpotensi mengancam integrasi bangsa seperti saat ini, fungsionalis struktural yang identik dengan genre jurnalisme damai lebih tepat digunakan. Pada situasi lain bisa menggunakan pendekatan konflik sebagai terapi kejut guna mendorong wacana publik menuju keharmonian.
Untuk bisa memilih di antara dua strategi itu membutuhkan kecerdasan intelektual yang cukup seorang jurnalis, apalagi bila jurnalis memilih strategi konflik dalam membingkai berita. Salah dalam mengambil strategi dalam mengonstruksi realitas konfliktual, akan berbahaya karena bisa mendorong publik menuju disharmoni sosial. Berbekal sertifikat “kompeten” Dewan Pers yang dipegang jurnalis saja tak cukup tanpa dibarengi kompetensi menganalisis sosial yang mumpuni.
Pada 9 Februari pekan lalu sebagian jurnalis merayakan Hari Pers Nasional (HPN). Lepas dari kontroversi penetapan HPN, ada baiknya momentum itu digunakan para jurnalis dan pengelola media untuk mengasah kembali kepekaan dalam menganalisis masalah. Kita buka lagi lembaran-lembaran karya pendiri jurnalisme damai, Johan Galtung itu.
Sebagai penutup, saya jadi teringat tokoh pers dunia, Joseph Pulitzer, sebagaimana dikutip Wibowo (2009). Dia mengatakan media (dia menyebut “surat kabar”-red) tanpa etika bukan hanya tak mampu melayani khalayak, melainkan justru berbahaya bagi khayalak. Selamat Hari Pers Nasional bagi yang merayakan…
Penulis :
Sholahuddin
Manajer Litbang Harian Solopos
Aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Solo
*) Artikel ini pernah dimuat di Harian Solopos edisi Senin (13/2/2017)




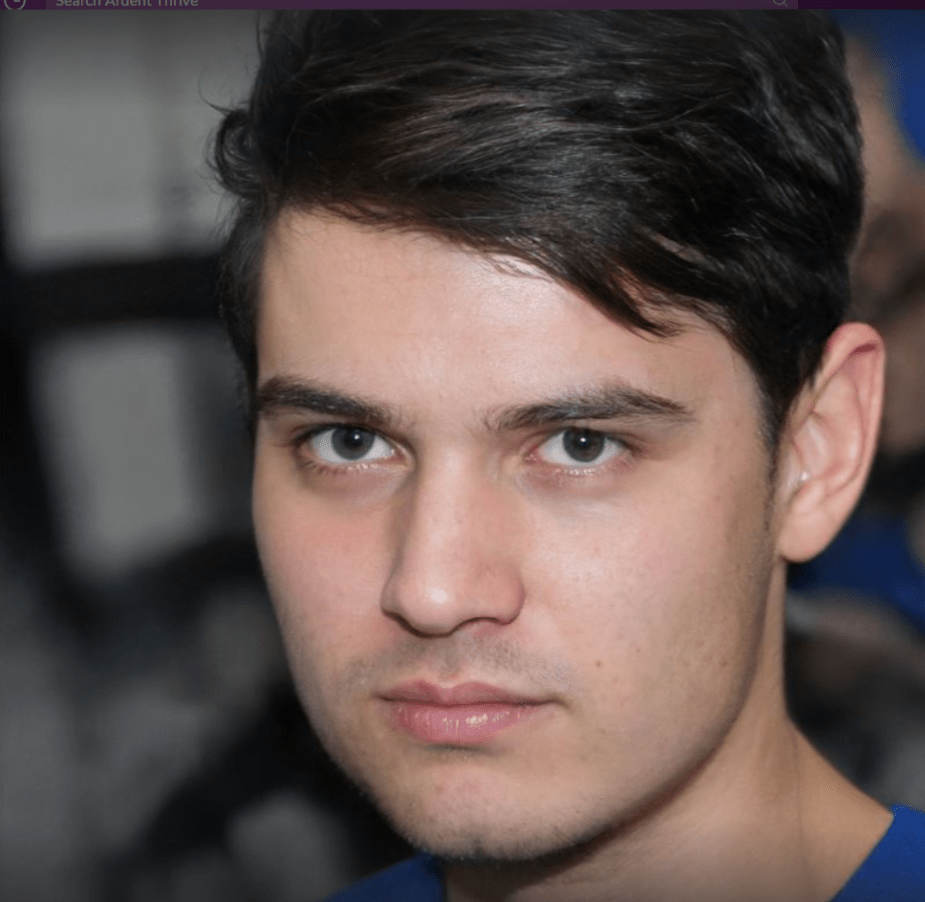
Add comment