Jurnalisme adalah subjektivitas. Jangan menggugat dulu. Pertama-tama, jurnalisme adalah aktivitas yang dilakukan jurnalis. Dalam aktivitas itu jurnalis tak bisa lepas dari subjektivitas.
Subjektivitas itu bisa berlatar belakang agama, pendidikan, pengalaman, bacaan, interaksi, lingkungan, komunitas, dan lain sebagainya. Kian banyak “subjektivitas” yang dimiliki jurnalis kian kayalah dia.
Kekayaan subjektivitas ini akan menentukan kemampuan jurnalis merumuskan “kode perilaku” yang diturunkan dari kode etik jurnalistik/jurnalisme. Sumber kode etik tentu saja nilai-nilai universal yang menjadi kerangka hidup manusia yang berkemanusiaan.
Bila dibahas lebih panjang dan lebar acap kali akan mengemuka pengalaman berbeda-beda di kalangan jurnalis ketika harus merumuskan kode perilaku yang menuntun dia menjalankan aktivitas jurnalisme yang ujungnya adalah berita yang dibaca, didengar, atau dilihat audiens.
Kita batasi saja konteks ruang dan waktu ihwal “subjektivitas” ini dalam tema pernikahan gay di Boyolali. Menurut saya ini menarik, dan penting, karena kemampuan jurnalis merumuskan kode perilaku dalam kegiatan jurnalisme dengan tema pernikahan gay di Boyolali ini akan menentukan banyak hal.
Di media sosial ada seorang kawan saya, dulu jurnalis di Kota Semarang, sekarang saya tak tahu apakah dia masih jurnalis atau tidak, menulis status “Boyolali heboh!”. Konteksnya tentu saja pemberitaan pernikahan gay itu.
Seorang kawan saya lainnya, bekas anggota DPRD Jawa Tengah, yang tinggal di Boyolali, mengunggah berita tentang pernikahan gay itu dan memberikan “afirmasi khusus” ihwal pernikahan sesama jenis itu.
Subjektivitas jurnalis ketika “menghadapi” fakta pernikahan gay, laki-laki yang punya orientasi seksual dengan sesama laki-laki, bisa saya pastikan, dibangun oleh latar belakang keyakinan atau agama yang dia anut dan kerangka budaya tempat dia lahir, tumbuh, dan berkembang.
Subjektivitas ini akan bertemu dengan kaidah nilai-nilai berita yang bisalah disebut sebagai laku dan pedoman mengobjektifkan laku jurnalis menjalankan jurnalisme. Saya berani memastikan, dalam perpaduan subjektivitas dan pedoman mengobjektifkan itu yang mengemuka cuma satu hal, eh dua hal, yaitu kontroversi dan konflik.
Kontroversi muncul dari pemahaman mayoritas masyarakat kita bahwa jenis kelamin dan orientasi seksual itu hanya dibangun oleh dua hal: laki-laki dan perempuan. Laki-laki harus berorientasi seksual terhadap perempuan, perempuan harus berorientasi seksual terhadap lakl-laki. Ketika ada laki-laki berorientasi seksual terhadap laki-laki atau perempuan terhadap perempuan, yang muncul ya kontroversi, sekontroversial ada manusia kok berkaki empat dan bertangan dua.
Konflik muncul dari pemahaman ihwal kontroversi tadi. Dari yang kontroversial itu mengemuka konflik antara pemahaman masyarakat luas dengan realitas atau fakta yang dihadapi, yaitu pernikahan gay. Dua hal ini yang membuat jurnalis “tertarik” menjadikan fakta yang dia hadapi, yaitu pernikahan gay di Boyolali, sebagai berita.
Kektika kekayaan subjektivitas si jurnalis berbeda-beda, kerangka pemberitaannya tentu akan berbeda pula. Jurnalis yang dominan “dikuasai” pemahaman doktrin bersumber agama pasti, saya berani memastikan nih, akan berpemahaman pernikahan gay itu “menyimpang”, “tidak benar”. “kotor”, “sampah”, “harus diluruskan”, “tak sesuai pemahaman masyarakat”. Kerangka demikian ini membuat jurnalis punya subjektivitas bahwa pernikahan gay itu “sangat menarik”, ya kerangka menariknya itu tadi…
Demikian pula dengan jurnalis yang subjektivitas memandang pernikahan gay ini didominasi keyakinan “jamak” masyarakat luas bahwa laki-laki ya seharusnya suka dengan perempuan dan perempuan ya seharusnya suak dengan laki-laki.
Kekayaan subjektivitas yang demikian ini akan menghasilkan berita yang sifatnya memberikan stigma kepada dua laki-laki yang “menikah” itu. Bila stigma dalam berita ini diulang-ulang dengan berbagai sudut pandang, misalnya afirmasi oleh tokoh masyarakat, tokoh agama, psikolog, dan lain sebagainya pasti akan berujung pada “penistaan”.
Nah, term terakhir itu yang berbahaya dalam konteks ruang dan waktu di Soloraya, bahkan di Indonesia, yang mayoritas warganya adalah muslim (yang mayoritas punya pemahaman “tak punya toleransi” terhadap homoseksualitas) dan berpemahaman budaya laki-laki itu jodohnya ya perempuan dan perempuan jodohnya ya laki-laki.
Kita bisa membayangkan apa yang akan terjadi pada dua laki-laki gay itu. Kemungkinan-kemungkinannya adalah: diusir dari rumah, diusir dari kampung halaman, didatangi rombongan orang yang meyakini homoseksualitas sebagai kotoran dunia dan akhirat, atau malah mereka berdua akan dibunuh.
Jurnalisme menghendaki jurnalis punya kekayaan subjektivitas yang berlimpah ruah sehingga mampu merumuskan kode perilaku sebagai terjemahan kode etik bersumber nilai-nilai universal untuk “mengolah” fakta yang dihadapi.
Dalam ruang dan waktu pembahasan ini, Aliansi Jurnalis Independen memberikan panduan pada Pasal 16 Kode Etik Aliansi Jurnalis Independen: Jurnalis menolak kebencian, prasangka, sikap merendahkan, diskriminasi, dalam masalah suku, ras, bangsa, jenis kelamin, orientasi seksual, bahasa, agama, pandangan politik, orang berkebutuhan khusus atau latar belakang sosial lainnya.
Saya berpemahaman, Anda boleh tak setuju, ketika jurnalis beraktivitas, menjalankan jurnalisme, harus sudah selesai dengan subjektivitas-subjektivitas diri sendiri sehingga mampu merumuskan kode perilaku yang memenuhi tuntutan–yang mustahli–bahwa jurnalis harus “objektif”.
Dalam tataran teknis–sesuai kerangka ruang dan waktu pembahasan ini–jurnalis mampu menghasilkan berita tentang pernikahan gay yang nirstigma, nirpenistaan, tentu tanpa keharusan membela.
Saya punya tesis, yang harus dibuktikan, ketika dua orang gay itu “menikah” dan nekad membuat acara yang berakibat “pernikahan” keduanya ketahuan wartawan–dengan segala konsekuensinya tentu–karena mereka ingin mendapat pengakuan, mendapatkan ruang, sehingga mereka bisa “menikmati” hidup mereka.
Dalam konteks ini, jurnalis tak punya hak menistakan mereka, menstigma mereka, dan juga tak punya kewajiban membela mereka. Tapiiiii, jurnalis punya kewajiban membela mereka, ketika “pernikahan” mereka yang “terbuka” itu berbuah tindak kekerasan, penganiayaan, atau laku-laku nirkemanusiaan lainnya. Ingat, mereka juga manusia, manusia seutuhnya. Mereka punya hak sipil, hak perdata, dan hak kemanusiaan.
Susah ya….? Begitulah, jurnalisme memang susah. Ya cuma orang-orang cerdas dan bernurani saja yang bisa menjalankannya. Intinya, jangan sampai pemberitaan tentang “pernikahan” gay itu berbuah “penistaan” terhadap mereka. Sudah ah, kepanjangan…..
Jurnalis, Jurnalisme, Homoseksualitas
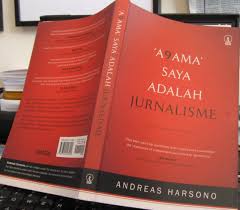





Add comment